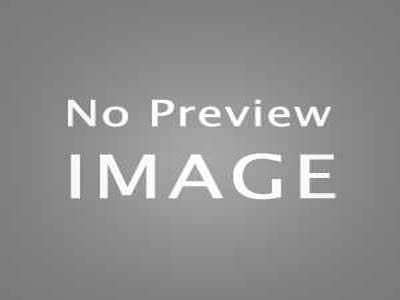Pada 11 September 2010 ini, seluruh umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Agar bisa berlebaran di kampung halaman, orang rela antri dan terjebak di perjalanan. Bahkan, mereka rela menghabiskan uang yang mereka kumpulkan dari bekerja keras selama setahun. Apakah lebaran di kampung halaman sebuah keharusan?
Meski Syafrida Yunis (42 tahun) berpenghasilan pas-pasan di Kota Bogor-Provinsi Jawa Barat, namun hampir setiap hari raya Idul Fitri (lebaran), ibu yang memiliki dua orang putra ini, berupaya pulang kampung ke Kota Padang-Provinsi Sumatera Barat.Di kampung halaman sendiri, waktu yang dapat dimanfaatkan Syafrida pun tak berapa lama. Bila dihitung-hitung, mungkin Syafrida bersama dua orang anaknya lebih banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Terkadang, bila tak dapat tiket bus jurusan Bogor – Padang, ia terpakasa ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru menuju Kota Padang.
Lantaran tingkat arus mudik juga membludak—terutama menjelang H 7—maka tak jarang pula ia terperangkap di pelabuhan penyeberang Merak. Pengalaman itu, hampir tiap tahun dialami Syafrida. Namun anehnya, ia bersama ke dua orang anaknya tak pernah kapok untuk mudik lebaran.
Kenyataan yang sama juga tak jarang dialami Irwandi (40 tahun), tiap kali pulang mudik lebaran. Hampir tiap tahun pria yang berprofesi sebagai pedangang kaki lima di Tanah Abang-Jakarta ini memboyong istrinya-Neneng (40 tahun) dan empat orang anaknya ke kampung halamannya di Batang Kapeh-Kabupaten Pesisir Selatan.
Bahkan kata pria yang akrab disapa Ujang ini, ia malah sengaja bekerja keras untuk mendapatkan uang, agar bisa berlebaran di kampung halaman. Dikatakannya, untuk menghemat pengeluaran, biasanya ia sengaja merental mobil.
“Dengan mobil rental itu, langkah kami menjadi ‘ringan’. Lagi pula, saya dan keluarga bisa sedikit santai,” kata Ujang.
Muhammad Ruslan (55 tahun), seorang pedagang Nasi Ampera di Jakarta, juga punya kebiasan yang sama. Bahkan Urang Sumando Muaro Labuah-Kabupaten Solok Selatan ini, tanpa sadar uang dikumpulkan selama setahun, bakal habis untuk lebaran yang hanya berlangsung beberapa hari saja.
Coba bayangkan, katanya dari tahun ke tahun (setiap lebaran), ongkos angkutan (bus, pesawat dan kapal laut) sangatlah mahal. “Bahkan, untuk memperolehnya, kita harus mendaftar dulu jauh-jauh hari,” ungkap Muhammad Ruslan.
Dikatakan pria yang memiliki 3 orang putra putri ini, karena takut tak kebahagian tiket, ia lebih sering merental mobil sewaan. Lagi pula, dengan mobil sewaan itu akan menambah nilai plus terhadap dirinya saat pulang kampung.
”Bilo pulang jo oto, urang di kampuang akan manyangko awak alah sukses di rantau urang. (Bila pulang dengan mobil, orang di kampung akan mengira kita telah meraih sukses di rantau orang,” ujar pria kelahiran Solok, 12 Juli 1955 ini.
Fenomena rame-rame mudik lebaran ini, mendapat tanggapan dari pengamat sosial Universitas Ekasakti Padang Provinsi Sumatra Barat-Drs Tarma Sartima MSi Kata Tarma, fenomena mudik lebaran ini termasuk kebiasaan yang unik. Sebab, bisa dibayangkan berapa tabungan selama beberapa bulan kerja, akhirnya berpindah format dalam bentuk konsumsi sandang, pangan atau sekedar oleh-oleh bagi keluarga atau kenalan di kampung halaman.
“Melihat kenyataan ini, setidaknya realita menunjukkan bahwa sejarah mengajarkan pada kita bahwa himbauan hampir tak pernah efektif. Kendati begitu, baiknya juga kita mengingat bahwa tradisi pengeluaran berlebihan tersebut bukanlah sebuah kebiasaan yang sehat,” kata Tarma Sartima.
Bila melihat kenyataan mudik lebaran itu, kata Tarma lagi, akan muncul pertanyaan; ‘bukankah lebih baik bila uang yang ada yang telah dikumpulkan sejak lama itu, digunakan untuk aktivitas produktif’.
“Saya rasa, jika harus ‘buang-buang uang tak karuan’, mungkin ada baiknya uang tersebut dikirimkan saja ke kampung halaman untuk sanak saudara dan handai taulan,” ungkap pria jebolan Universitas Gajah Mada ini sambil tersenyum.
Paling tidak uang itu, kata matan Dekan FISIP Universitas Eka Sakti Padang ini, dapat mendorong perekonomian pedesaan. Sebab, dalam realitanya, kebiasan menghabis-habiskan uang itu, sama tak membawa manfaat positif. Ia hanya memberikan justifikasi pada konsumerisme.